Interkoneksi di Masa Lalu, Toleransi di Masa Kini
Tulisan ini hadir untuk mengapresiasi ruang screening yang “nyempil” dalam agenda besar BWCF. Di sisi lain, saya juga berupaya memberikan kritik untuk film-filmnya secara lebih khusus. Dengan begitu, saya bisa turut serta dalam perbincangan seni dan sejarah. Terutama, yang menggunakan film sebagai mediumnya.
FESTIVALNASIONAL
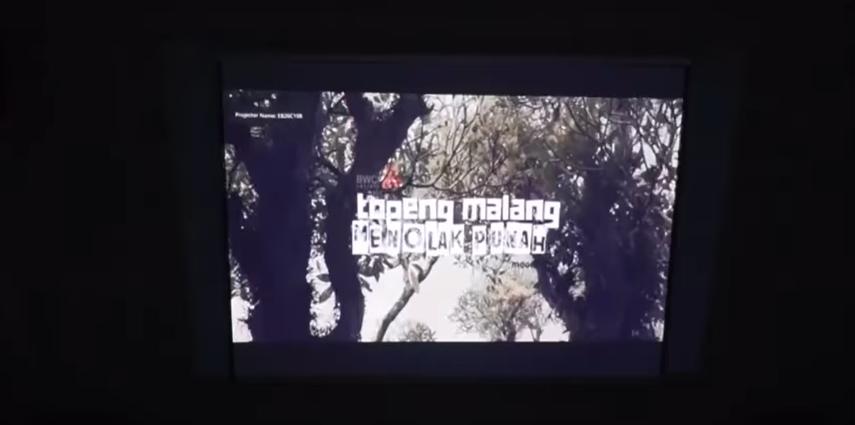
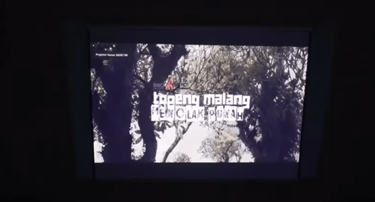
Sejarah dan Seni Berpadu dalam Film-Film BWCF 2023.
BeritaSinema.com - Borobudur Writers and Cultural Festival telah berakhir pada Senin (27/11) lalu. Esok harinya, saya pergi naik angkot LG ke arah Alun-Alun Kota Malang dan turun di Riche Hotel. Hari itu saya membuat janji temu dengan Mas Seno Joko Suyono. Seorang pewarta, akademisi, dan budayawan – begitu hasil pencarian Google mendiskripsikannya. Namun, yang paling utama, beliau adalah pendiri BWCF.
Tujuan saya bertemu adalah untuk mengetahui lebih banyak film-film yang tayang. Dalam lima hari pelaksanaan acara, setidaknya ada enam film yang ditayangkan. Tiga film panjang dan tiga film pendek. Sebagian besar agenda BWCF adalah simposium dan ceramah umum. Topik-topiknya berkisar pada sejarah dan arkeologi. Ada pula Podium Sastra untuk ekspresi kesusastraan. Namun, penayangan film rupanya tidak ketinggalan. Sebagian dari film yang tayang diproduseri oleh Mas Seno sendiri dan BWCF Society. Sebagian yang lain diputar agar tayang pertama kali dalam agenda tahun ini.
Tulisan ini hadir untuk mengapresiasi ruang screening yang “nyempil” dalam agenda besar BWCF. Di sisi lain, saya juga berupaya memberikan kritik untuk film-filmnya secara lebih khusus. Dengan begitu, saya bisa turut serta dalam perbincangan seni dan sejarah. Terutama, yang menggunakan film sebagai mediumnya.
Interkoneksi
Ada satu ciri utama dalam film-film yang tayang dalam agenda BWCF ke-12 ini. Keterhubungan lintas teritori dan ideologi yang inspirasinya diambil dari sejarah. Di hari pertama, kita mendapat suguhan dari sutradara Nia Dinata, Unearthing Muarajambi. Dokumenter panjang ini mengisahkan kehidupan masyarakat yang berdampingan dengan munculnya situs-situs arkeologi.
Masyarakat Muarajambi dikisahkan memiliki kepedulian terhadap situs-situs tersebut. Mereka ikut mengelola pariwisata dan menerima tamu-tamu yang datang berziarah. Dalam diktat sejarah, seorang pelajar Buddhis terkenal bernama I Tsing berguru ke sana. Dalam Muarajambi bertutur, sejarah dihadirkan dalam animasi bercorak wayang, bergerak dalam stop motion. Nama-nama situs dan tokoh dilukis secara majikal.
Untuk menunjukkan kredibilitas tanpa menggurui, wawancara seorang sejarawan dihadirkan dalam bingkai yang memikat. Tidak hanya berdiam diri di Muarajambi dengan segala perkembangan pariwisata dan layanan religiusnya. Film ini juga mengikuti dua warga lokalnya menelusuri catatan sejarah I Tsing. Bergerak ke India dan Tibet. Bahkan bertemu dengan Dalai Lama.
Keterhubungan sejarah lebih ekspresif di hari kedua dalam sebuah film tari berjudul Mahendraparvata. Dua orang penari dari Kamboja masing-masing membawa sebuah topeng. Keduanya ditarik untuk menelusuri situs-situs arkeologi yang didirikan Jayawardana II. Konon, sang Raja terkesima dengan Borobudur dan berharap bisa membangun situs serupa. Kedua buah topeng itu simbol pekerja yang ingin pulang dan kembali ke tanah aslinya. Untuk itu mereka dilarung ke laut. Pulang ke tanah air.
Sebagaimana kisah panji, dua topeng itu terpisah dan ditemukan kembali oleh orang berbeda. Mendengar suara hati dari topengnya, kedua penari di Jawa membawa mereka bertemu. Mereka menelusuri situs-situs seperti Gereja Ayam, Borobudur, dan berakhir di Sungai Elo Magelang. Ditakdirkan sebagai sepasang kekasih, kedua topeng itu kembali dilarung. Tugasnya sebagai pencerita sejarah telah tuntas.
Diadakannya BWCF di Malang adalah untuk memperingati setahun kepergian Ibu Dr. Edi Sedyawati. Bekas Dirjen Kebudayaan periode 1993-1998 itu wafat pada 22 November. Di tahun 2010, ia turut serta diwawancarai dalam film dokumenter berjudul Presenting Indonesia. Film ini mengisahkan tentang “Misi Kesenian ke Mantja Negara” selama Presiden Soekarno berkuasa. Khususnya pada tahun 1952-1965.
Seniman-seniman muda berbakat dari penjuru Indonesia dikumpulkan di Istana Negara. Mereka saling belajar tarian daerah dan dikirim dalam misi-misi diplomasi kebudayaan. Ingatan akan momen itu bahkan tetap disimpan. Mereka mengingat bagaimana sulitnya terbang jauh menggunakan kapal dan pesawat militer. Mereka menari siang malam berhari-hari menampilkan tarian yang sama. Dan ketika mendapat sedikit libur, mereka takjub dengan negeri yang mereka kunjungi.
Tidak jarang bahwa dalam satu misi mereka mengunjungi lebih dari satu negara. Sri Lanka, Uni Soviet, Tiongkok, Jepang, Amerika dan yang paling dekat Singapura. Narasumber-narasumber dalam film ini masih ingat tarian yang mereka tampilkan. Mereka menyanyikan kembali lagu dengan percaya diri. Bahkan kerja-kerja dekorasi yang mereka lakukan tak pernah mereka lupakan. Ibu Edi Sedyawati adalah salah satunya. Potongan video wawancaranya ditampilkan dalam acara pembukaan. Film lengkapnya dihadirkan di hari ketiga.
Bukti keterhubungan lain yang bisa ditemukan di hari keempat. Selasih: Wanita dengan 11 Nama dan Genti Malay Betawi Portugis ditayangkan berurutan. Film pertama menceritakan tokoh kesusastraan asal Sumatera Barat. Kiprahnya menurun setelah ditangkap pemerintah Soekarno karena dianggap terlibat dalam Pemberontakan PRRI. Film kedua menceritakan identitas komunitas Betawi Portugis di Jakarta.
Subjek filmnya mungkin cukup terbatas: suatu masyarakat atau seorang tokoh. Namun sejarah Betawi Portugis begitu panjang. Nama-nama fam mereka campuran dari berbagai bahasa. Makanan dan musik mereka perbedaannya kentara. Penonton akan bingung mendapati budaya siapa mengikuti siapa. Nyatanya, budaya kita hari ini sudah lebur membaur. Identitas kita tuliskan untuk mengingat asal-usul diri kita.
Toleransi
Salah satu kritik yang cukup mengemuka dalam film Mahendraparvata adalah pesannya yang kentara. Sebagai suatu film, fiksi terutama, pesan itu nomor dua. Nomor satunya cerita. Namun, pesan toleransi mudah dilihat dari adegan pelarungan dua topeng di Sungai Elo. Tak hanya penari, hadir pula lima pemimpin dari setiap agama. Adegan-adegan serupa selalu dinarasikan dalam dialog lintas-iman atau forum kerukunan beragama. Seolah-olah kalau kelima pemimpin agama didatangkan, kerukunan sudah dapat ditunaikan.
Interkonektivitas adalah bahan: mencapai toleransi adalah tujuannya. Dengan menunjukkan keterhubungan lintas teritori dan ideologi, kita diharapkan bisa mencontoh masa lalu. Semua orang hidup rukun dalam perbedaan dan hidup tanpa diskriminasi. Namun, yang sering diabaikan adalah masa lalu tidak sepenuhnya damai. Kita "merasakan damai" pada hari ini karena tidak menginginkan masa lalu terulang. Hanya menunjukkan keterhubungan bukan berarti pesan perdamaian dapat tersampaikan. Keterhubungan dalam adegan-adegan itu artifisial. Sebagaimana pembangunan lima rumah ibadah berbeda secara berderetan.
Muarajambi Bertutur melakukan hal serupa, namun dengan contoh yang lebih organik. Meskipun berlatar masyarakat muslim, mereka tidak segan menerima tamu dari Tibet atau Thailand. Layanan pariwisatanya mendasar: penginapan, ojek motor, hingga matras untuk berdoa. Pelestarian alam, kerja-kerja pemugaran dan layanan pariwisata mungkin tampak komersil. Namun, dengan turut serta memelihara candi, mereka menjadi contoh terbaik toleransi.
Pemutaran Film Topeng Malang Menolak Punah


Fariduddin Aththar (kiri) kontributor BeritaSinema.com bersama Seno Joko Suyono (Founder BWCF).
Film sebagai Presentasi
Dialog tentang representasi dalam film sudah jamak dilakukan dan masih akan terus bergulir. Pertanyaannya adalah apakah yang terjadi dalam film sesuai dengan kenyataan? Apakah film adalah cermin realitas? Pendapatnya bermacam-macam dan filmmaker punya kebebasan fiksional untuk mewujudkannya. Namun, film tidak serta merta merupakan presentasi atau penyampaian informasi. Medium film seharusnya menjadi suatu seni audio-visual yang mampu memikat penonton dan menggugahnya.
Dengan bahan sejarah yang kaya dan basis riset mendalam, film-film BWCF mirip presentasi. Ada judul, sub-judul, argumen utama, lalu detail-detail penjelas. Kalaupun dokumenter berkembang dari esai, ia tidak sepenuhnya ditranslasikan sebagai esai. Mahendraparvata menceritakan candi-candi secara tekstual. Begitu pula situs-situs di Indonesia: Gereja Ayam dan bekas seminari yang dibakar Belanda. Keduanya tidak memiliki relasi langsung dengan cerita di Kamboja. Namun keduanya tetap dirasa penting untuk disampaikan.
Jennifer Lindsay melalui Presenting Indonesia melakukan hal serupa. Bab-babnya mirip buku: Mula dan Kenangan, Tudjuan, hingga Kenapa Misi Kesenian? Setiap narasumber memberikan sumbangsih yang berbeda dalam setiap bab. Namun, alasan paling mungkinnya adalah latar belakang Lindsay sebagai penerjemah. Karya-karya terjemahannya merentang dari Butet Kertaradjasa hingga Goenawan Muhammad. Oleh karena itu, hasil dokumenternya sederhana: bertanya - dijawab - memberikan foto keterangan.
Pemikiran tentang presentasi ini sebenarnya baru terpikirkan di hari keempat. Selasih: Wanita dengan 11 Nama membuat saya mengingat sistem presentasi di masa kuliah. Isinya kolase foto lama, kadangkala ada video. Narasi yang mengangkat "perasaan" divisualisasikan dengan animasi. Namun, kelemahan terbesarnya adalah voice-over (VO). Narator wanitanya berbicara dengan berapi-api, membuatnya tidak cocok dengan kisah Selasih kecil. Kalau dibayangkan, VO nya berlagak sebagai petugas bandara: profesional, elegan, dan mewah. Padahal, kisah Selasih adalah narasi perjuangan. Dia tidak serta-merta menjadi pejuang, tetapi meniti karir dalam lingkungan yang ketat.
Selain itu, kolase foto dan video diiringi dengan teks penjelas. Bukan subtitle di mana teks mengikuti narator. Di film ini, narator "membaca" teks yang terpampang. Benar-benar mirip presentasi. Sebuah presentasi yang tidak dilakukan dengan baik.
Apa alasan dari fenomena ini? FX Domini BB Hera, produser pelaksana film Selasih mengajukan jawaban. Kemungkinan besarnya adalah kebiasaan menjadikan film atau media audio-visual lain sebagai media ajar. Selasih pun diniatkan untuk itu, dengan target penonton anak sekolah menengah. Oleh karenanya, perlu ada alur judul-argumen-keterangan untuk mempermudah penonton sebagai pembelajar. Lagipula, latar belakang filmmakernya kebanyakan adalah studi sejarah dan arkeologi. Sistematika tersebut mungkin terus dipertahankan tanpa melihat adanya alternatif.
Lalu, apa alternatifnya? Cerita. Narasi. Riset yang mendalam dan sumber ilmiah yang bertumpah ruah akan terasa menggurui. Memasukkannya dalam sebuah tokoh akan membantu penonton menikmati cerita. Membenamkan riset dan bukti empiris akan sangat menyenangkan dalam alur yang mengasyikkan. Oleh karenanya, Mahendraparvata adalah fiksi. Namun di akhir, film ini berupaya menunjukkan keilmiahan dalam teks penjelas after credit.
Hal yang jauh menyenangkan dan terasa pas ditampilkan dalam Topeng Malang Menolak Punah. Dokumenter pendek garapan Moi Films ini menampilkan Nasa'i, pegiat topeng malangan. Sebagai peziarah, ia ingin sowan kepada para sesepuh pegiat kesenian yang terpinggirkan. Kunjungannya tidak terbatas pada mereka yang masih hidup dan mengepulkan asap rokok. Kubur-kubur sepi dan tenang juga menjadi destinasi ziarahnya. Tokoh-tokoh diceritakan dengan kontribusinya. Wawancaranya menenangkan ditemani musik syahdu yang terdengar sakral.
Dengan cerita perjalanan, Nasa'i tidak terasa menggurui: niatnya malah mengajak penonton belajar. Muarajambi Bertutur menggunakan hal serupa, dengan fokus pada masyarakat yang mereka rekam. Mengajak penonton belajar bisa menjadi alternatif yang bagus seiring dengan narasi sejarah sendiri. Bahwa, penemuan-penemuan arkeologis itu belum habis. Masih ada cerita-cerita terpendam yang menunggu untuk digali. Masih ada banyak materi pembelajaran yang bisa diungkap. Masih ada kekayaan sejarah yang dapat divisualisasikan.
Catatan terhadap Screening
Kembali pada aspek bahwa film bukan hanya media ajar, "pemutaran film" juga penting. Mengapa kemudian saya menyebut screening ini tampak "nyempil" adalah karena kapasitasnya. Mungkin memang bukan pemutaran film yang menjadi fokus agenda BWCF. Tapi, memperlakukan pemutaran agar layak untuk penonton adalah hal yang patut dilakukan.
Tidak ada panitia di meja depan. Tidak ada orang yang bisa saya tanyai tentang filmnya, siapa produsernya, kapan dibuatnya. Di website dan akun Instagram hanya ada informasi tempat dan waktu pemutaran. Mengandalkan Google, saya mencari tahu sendiri tentang Presenting Indonesia dan Mahendraparvata. Okelah kalau keduanya film lama. Tapi setidaknya ada panitia yang bisa saya tanya-tanya.
Padahal, pemutaran film ini mendapat atensi yang cukup besar. Hampir setiap film dipenuhi dengan penonton baik peserta maupun umum. Ada seorang guru yang mengajak murid-muridnya. Ada penonton yang rela menunggu di lorong meskipun salah jam. Itupun karena informasi di panitia dan peserta berbeda. Seorang panitia yang ditugaskan mengenakan earphone di kedua telinga. Dia bahkan melenggang pergi ketika seseorang menegurnya untuk bertanya. Jadi, memperlakukan pemutaran dengan layanan yang lebih baik tampaknya layak dicoba. Setidaknya, dengan menugaskan panitia dengan sumber informasi yang cukup.
Sesi apresiasi dilakukan dengan cukup baik, meskipun baru muncul di dua hari terakhir. Unearthing Muarajambi tayang di hari pertama, namun diskusinya dilakukan besoknya di tempat berbeda. Selain itu, saya berterimakasih banyak terhadap pemutaran film. Tidak ada tiket masuk, lokasi mini theater yang memadai, hingga layaknya kualitas audio-visual. Ke depan, semoga BWCF bisa menyediakan layanan pemutaran yang lebih baik. Screening bukan hanya menyediakan film sebagai media ajar, tetapi juga media pemantik kajian. Doa terakhir saya mengiringi agenda BWCF selanjutnya untuk selalu sukses. Begitu pula rencana produksi film-film non-komersil yang tetap diputar secara alternatif.
Saya pamit kepada Mas Seno dan melanjutkan perjalanan menyusuri Kayutangan. Terimakasih telah datang di Malang! (FA/K1/FA)
